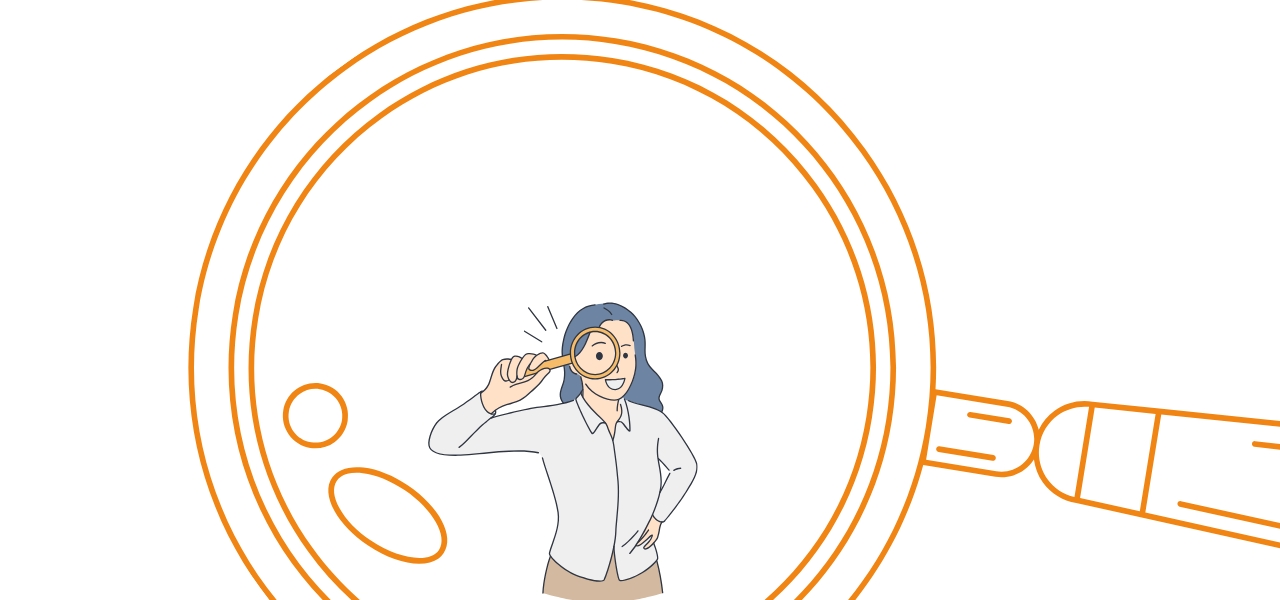Oleh: Abdul Rosyidi
Dalam sebuah diskusi tentang kekerasan terhadap perempuan, ada anggapan bahwa kekerasan seksual hanyalah bagian kecil dari persoalan besar diskriminasi dan subordinasi perempuan. Pendekatan ini menganggap bahwa fokus pada kekerasan seksual saja tidak cukup menyentuh akar masalah, yakni sistem patriarki yang melanggengkan ketimpangan kuasa dan norma-norma diskriminatif terhadap perempuan.
Fokus hanya pada kekerasan seksual tanpa mengkritisi akar strukturalnya memang akan berisiko mengobati gejala, bukan mengatasi sumber penyakit. Argumen ini valid karena kekerasan seksual tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks kehidupan dan kebudayaan di mana terdapat relasi kuasa yang timpang di dalamnya.
Meskipun argumen tersebut memiliki dasar, akan tetapi kita tidak bisa menyebut kekerasan seksual sebagai “masalah kecil” atau “bagian kecil saja”. Mengapa demikian? Pandangan seperti ini berisiko mengecilkan urgensi dan dampak nyata yang dialami orang yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, menganggap kekerasan seksual sebagai masalah kecil akan menutup peluang strategis untuk melakukan transformasi sosial.
Kekerasan seksual bukan “masalah kecil” yang bisa dikesampingkan atau diperlakukan sebagai isu sekunder karena dampaknya sangat luas dan menghancurkan. Ingat, kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan paling sering dialami perempuan. Menangani kekerasan seksual secara serius berarti membuka jalan untuk menggugat relasi kuasa dan norma-norma budaya patriarkal di tengah masyarakat kita.
Artinya, bekerja pada isu kekerasan seksual justru bisa menjadi “pintu masuk strategis” untuk membongkar akar diskriminasi yang lebih luas di berbagai lini kehidupan masyarakat kita. Misalnya kasus kekerasan seksual di sekitar kita –baik di kampus ataupun lembaga pendidikan keagamaan—akan membuka lipatan-lipatan struktur soal norma, moral, budaya, impunitas, dan ketimpangan kuasa. Pemahaman terhadap lipatan-lipatan itu memahamkan kita terhadap aspek-aspek kebudayaan yang menimbulkan masalah hari ini.
Kekerasan seksual merupakan wajah paling brutal dari patriarki. Ia adalah bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan, dan memiliki dampak multidimensi: psikologis, sosial, ekonomi, hingga politik. Menangani kekerasan seksual secara serius justru membuka jalan untuk membongkar akar diskriminasi dan relasi kuasa yang timpang dalam kebudayaan kita. Dalam konteks ini, pengalaman Umah Ramah menjadi relevan sebagai contoh konkret bagaimana isu kekerasan seksual bisa menjadi titik masuk penting dalam perjuangan melawan sistem yang tidak adil.
Umah Ramah merupakan komunitas yang bekerja dalam isu kekerasan seksual berbasis komunitas. Kerja-kerja Umah Ramah tidak hanya berkutat pada penanganan kasus individual, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui pendekatan yang interseksional, kritis, dan berpusat pada orang yang mengalami dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan rahmatan lil ‘alamin.
Pertama, melalui “pemulihan” (kalau bisa disebut demikian) berbasis komunitas, Umah Ramah menekankan bahwa orang yang mengalami tidak bisa dipulihkan hanya melalui jalur hukum yang kerap kali traumatis. Apalagi sistem hukum dan aparat di negara kita masih sebatas menjalankan fungsi retributifnya. Dalam sistem ini, orang yang mengalami tidak menjadi perhatian utama karena tujuan utama sistem hukum kita adalah untuk menghukum pelaku. Maka sering sekali kita mendengar pada setiap tindak hukum, selalu ada tujuan untuk membuat pelaku menjadi jera.
Hal ini bukan berarti tindakan di jalur hukum itu keliru. Akan tetapi, Umah Ramah memposisikan diri untuk bekerja di ruang lingkupnya di grassroot dan meyakinkan publik bahwa kerja ini bisa dilakukan siapa saja.
Bagi kami, selain tindakan hukum, penting menyadari bahwa lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat, harus menjadi bagian dari proses pemulihan. Dengan membangun dukungan kolektif seperti itu, Umah Ramah sebenarnya secara sadar dan aktif ikut melawan budaya menyalahkan korban dan menormalisasi kekerasan, menggugat patriarki secara nyata.
Kedua, Umah Ramah secara konsisten membangun kesadaran kritis dan humanis di dalam komunitas. Kami membongkar akar-akar kekerasan seksual seperti relasi kuasa yang timpang, maskulinitas toksik, dan norma-norma budaya yang mendiskriminasi perempuan mulai dari diri sendiri. Edukasi dan diskusi komunitas menjadi ruang untuk menyadari bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah struktur.
Sebagai contoh, Umah Ramah menggunakan pendekatan yang ramah terhadap tradisi, akan tetapi kami menggunakan pendekatan kritis dan humanis terhadapnya. Tradisi tertentu bisa jadi tidak bisa kita sebut sebut kearifan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada kondisi demikian kearifan menjadi ketidakarifan lokal.
Sehingga tidak semua adat adalah baik dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan saat ini. Gampangnya, tidak semua adat adalah kearifan, dan tidak semua tradisi layak dipertahankan. Kuncinya adalah apakah praktik tersebut menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah juga bisa membuat kearifan lokal justru “digunakan” untuk menyalahkan orang yang mengalami atau menormalisasi kekerasan seksual. Budaya patriarki juga bisa mengedepankan pemeliharaan “nama baik”, “kehormatan lembaga”, atau “kehormatan keluarga” daripada mengutamakan keadilan bagi orang yang mengalami.
Tentu kita bisa mengenali berbagai tradisi, budaya, atau bentuk-bentuk “keadiluhungan masa lalu” di tempat kita sendiri. Umah Ramah sendiri menemukan lapisan-lapisan budaya itu itu di tempat-tempat kami hidup, misalnya di pesantren, kampus, lembaga, dan di komunitas-komunitas lainnya di tengah masyarakat.
Di tengah sistem dan lapisan-lapisan kebudayaan itu, kami selalu berpegang pada prinsip bahwa tradisi yang bisa menjadi bahan bakar transformasi mempunyai tujuan untuk menempatkan manusia –dengan apapun jenis kelaminnya—pada martabat kemanusiaannya. Jika ada yang tidak bertujuan seperti demikian, maka bisa jadi itu adalah sebentuk ketidakarifan dengan kedok kearifan lokal, tradisi, adat, atau budaya.
Keyakinan besar itu kemudian perlu dilakukan dalam usaha-usaha terkecil semisal yang dilakukan Umah Ramah saat berdiskusi dengan mahasiswa, santri, dan anak-anak muda tentang isu yang seringkali dianggap tabu: seksualitas dan kekerasan seksual. Lewat diskusi itulah kita bisa mengurai pada aspek mana saja “keadiluhungan” yang bersifat struktur itu menciptakan penderitaan nyata pada individu.
Ketiga, Umah Ramah memperjuangkan ruang aman di tengah masyarakat dan keberpihakan pada orang orang mengalami. Dengan konsep pemulihan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami meyakini bahwa membangun ruang aman bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga menciptakan lingkungan dan dunia yang mendukung dan memihak pada orang yang mengalami. Kerja besar itu bisa dimulai dari kerja-kerja kecil seperti kemauan untuk mendengarkan cerita orang yang mengalami, menjadi taman dan pendengar yang baik, dan tidak diam saat ada kekerasan seksual.
Selain itu, di tengah masyarakat yang sering diam, menormalisasi kekerasan, dan mengabaikan orang yang mengalami, keberpihakan terhadap orang yang mengalami juga menjadi langkah yang penting. Saat “kerja-kerja kecil” ini dilakukan secara sadar dan kritis, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai hanya “kerja sambilan” atau mengadvokasi “isu sekunder” belaka, melainkan upaya nyata dalam melawan patriarki serta diskriminasi dan subordinasi perempuan.
Keempat, Umah Ramah dalam kerja kebudayaan yang lebih luas –melalui kerja-kerja dalam isu kekerasan seksual—ingin meyakinkan masyarakat bahwa basis moral kita bermasalah. Selama ini, moralitas selalu dikaitkan dengan dengan tradisi dan kebudayaan, terlepas dari basis paling mendasarnya: human being.
Kita sering menyebut keluhuran budi pekerti sebagap tradisi ketimuran, akan tetapi berbagai praktik pengadaban dalam masyarakat kita memupuskan suara-suara individu yang mengalami kekerasan seksual. Atas nama pelestarian keadilihungan tradisi, moralitas kita mengabaikan penderitaan-penderitaan mereka. Misal, ajaran tentang pentingnya ketaatan terhadap guru dan orang tua membuat anak-anak dan remaja kita tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kehendak dirinya. Saat kehendak itu muncul, kita sering malebelinya dengan tidak sopan, tidak bermoral, atau bukan bagian dari adat ketimuran.
Moralitas harusnya “dibangun” dari basis pertamanya yakni menghapuskan penderitaan manusia, agar manusia-manusia ini berada pada martabatnya, bukan “dibangun” dari kodifikasi penafsiran elit. Selagi moral kita dibangun tidak pada pondasi kemanusiaan-nyata itu, maka segala upaya untuk menghapuskan diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan hanya akan mengulang-ulang pekerjaan serupa sebelumnya. Hasilnya, upaya ini hanya akan menciptakan elit-elit baru saja sementara masalah yang ingin diatasi masih tetap terjadi, bahkan semakin menjadi-jadi.
Sekali lagi, kekerasan seksual bukanlah isu kecil. Ia adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling nyata dan sistemik yang dihadapi perempuan. Bekerja dalam isu ini tidak berarti mengabaikan diskriminasi struktural—justru inilah medan perjuangan untuk membongkarnya. Umah Ramah telah menunjukkan bahwa dari luka dan penderitaan orang yang mengalami, kita bisa membangun gerakan yang menyembuhkan sekaligus menggugat sejak dari bawah.
Melalui pengalaman Umah Ramah, menjadi jelas bahwa bekerja dalam isu kekerasan seksual tidak bisa dianggap sebagai kerja yang terfragmentasi dan terbatas. Sebaliknya, ia adalah kerja sosial, kerja politik, kerja kebudayaan, dan kerja pembebasan. Dengan menangani masalah-masalah kekerasan seksual, kita sadar sedang (dan akan terus) menggugat struktur yang lebih besar—patriarki dan sistem sosial yang timpang. []