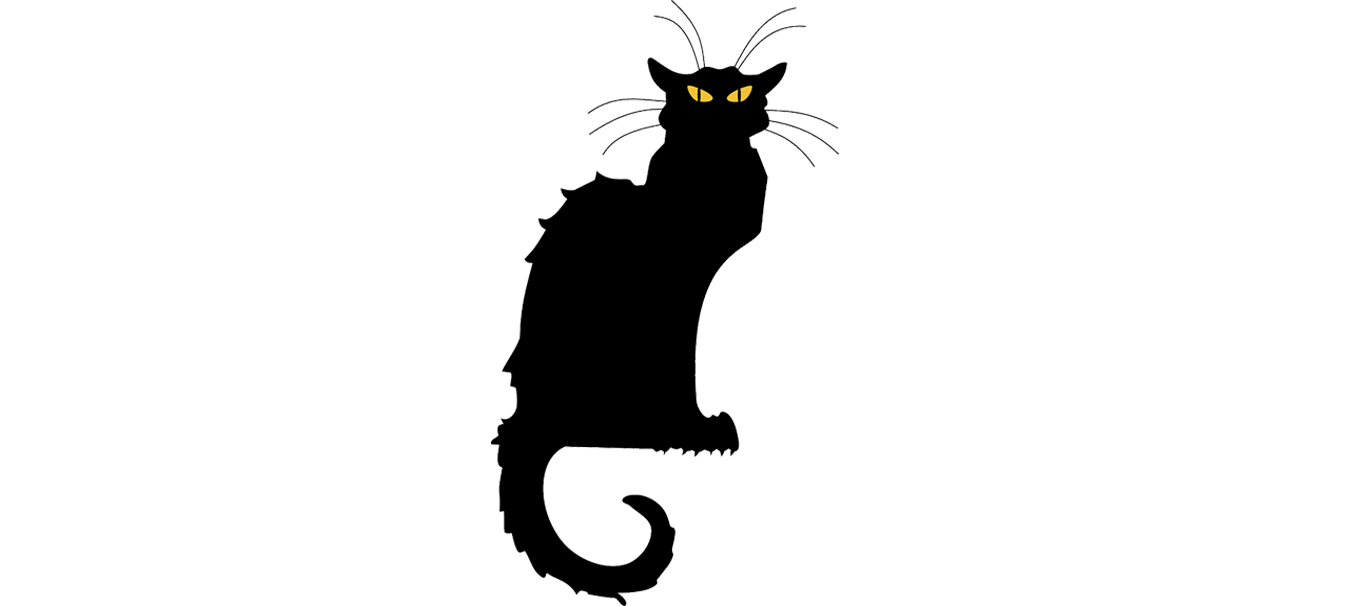Oleh: Winarno
Bintang Emon sempat membuat heboh jagat instagram (IG) beberapa waktu yang lalu. Lewat video berdurasi satu menit, komika itu berbicara pada netizen soal catcalling. Beragam respon pun bermunculan. Kebanyakan respon bernada positif termasuk diantaranya ada netizen yang berbagi pengalaman mendapatkan serangan catcalling. Ada yang lewat ungkapan, siulan, dan bentuk lainnya.
Ungkapan catcalling semisal “mau kemana neng?” “Hai, cewek”, “Ko sendirian saja, mau gak ditemenin?” “Halo cantik”, “Ihh pantatnya besar”, ” Payudaranya kelihatan tuh”, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, catcalling bisa juga berupa siulan “menggoda”, lirikan mata terhadap bagian tubuh, dan beberapa gestur tubuh lainnya, sehingga korban merasa tidak nyaman.
Meskipun kadang perbuatan tersebut sering disebut “pujian” oleh pelakunya, akan tetapi, baik sadar ataupun tidak, catcalling merendahkan derajat dan martabat manusia. Kenapa demikian? Karena perbuatan tersebut membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, dan merasa direndahkan.
Pada tahap tertentu, korban catcalling justru bisa mengalami ketakutan dan was-was ketika berjalan sendiri di tempat yang sepi atau ketika mereka harus berjalan melewati segerombolan laki-laki yang sedang nongkrong. Kekhawatiran itulah yang membuat korban akan membatasi kebebasan untuk bergerak dan beraktivitas di luar. Hingga berefek semakin lunturnya rasa percaya diri.
Jadi catcalling itu bukan pujian. Justru ia adalah bentuk pelecehan seksual non-fisik. Bahkan Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa catcalling merupakan salah satu dari 15 bentuk kekerasan seksual.
Harus diakui, pelaku catcalling memang didominasi oleh laki-laki. Namun tak menutup kemungkinan catcalling bisa dilakukan oleh perempuan. Meskipun faktanya, perempuan-lah yang seringkali menjadi korbannya.
Kenapa seringkali terjadi catcalling pada perempuan? Hal ini berakibat dari relasi yang tidak egaliter, tidak setara di berbagai lini kehidupan. Relasi timpang ini tentunya dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dimana laki-laki selalu ditempatkan pada posisi di atas, superior dan perempuan menjadi objek.
Parahnya, lantaran laki-laki berada di posisi atas, catcalling dianggap wajar, normal saja bahkan dalam kasus tertentu justru menyalahkan perempuan. Semisal “Pakaiannya seksi tuh”, ” payudaranya kelihatan”, dan lain sebagainya. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah inilah menyebabkan hal ini terus terjadi berulang-ulang. Bahkan perilaku ini bisa menjadi langgeng dan terus-menerus terjadi karena rape culture yang begitu kuat.
Catcalling Bisa Dilaporkan
Jika menelisik Undang-Undang terbaru menyangkut perempuan, yakni UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual bahwa kasus ini sebagai delik aduan. Menurut analisis penulis, catcalling bisa masuk pada pasal 4 (1) a yakni soal pelecehan seksual non-fisik. Jika terbukti sebagaimana termaktub dalam pasal 5, maka pelaku bisa terjerat pidana selama sembilan bulan dan atau kena denda paling banyak 10 juta rupiah.
Selain itu perundang-undangan di atas merupakan salah satu item dari substansi hukum. Karena ada hukum-hukum lainnya semisal hukum adat, agama dan lain-lain. Namun tak kalah pentingnya juga dari sistem hukum ini yakni struktur hukum seperti lembaga atau instansi penegak hukum dan budaya hukum berupa pandangan-pandangan atau kebiasaan baik penegak maupun masyarakat itu sendiri.
Jadi tiga sistem hukum ini harus diimplementasikan secara bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Namun bagi penulis, budaya hukum merupakan aspek dasar dari sistem hukum. Sebab hal ini dapat mempengaruhi secara struktur dan substansi hukum itu sendiri. Jadi aspek kultural atau kesadaran masyarakat penting agar supremasi hukum dapat ditegakkan, tidak tebang pilih.
Diamlah!
Soal menghentikan catcalling di masyarakat, penulis sepakat dengan gagasan Bintang Emon, yakni diam ketika melihat perempuan-perempuan berjalan, di kendaraan, maupun di medsos. Diam di sini berarti tidak melakukan tindakan, ucapan, gestur, dan lain sebagainya yang membuat perasaan perempuan tidak nyaman dan tidak aman.
Seperti telah disebutkan di atas, catcalling tidak hanya menimpa perempuan, tapi juga laki-laki. Karena hal ini soal relasi kuasa. Siapa yang berkuasa, berkelompok, maka catcalling bisa terjadi pada siapa saja, tanpa melihat jenis kelamin.
Dalam kasus ini, diam merupakan hal awal dalam rangka menghentikan kasus catcalling. Di samping banyak upaya dan cara lainnya agar catcalling pupus di lingkungan kita. Diam bukan berarti malas berpikir atau bertindak, tapi dalam kasus ini diam justru dapat membuat orang lain tidak direndahkan dan dirugikan.
Menjaga diri dengan diam merupakan bagian dari budi pekerti manusia. Sikap ini bukan hanya bentuk menghargai orang lain tapi juga menghargai diri sendiri. Ini soal cara pandang atau keyakinan diri, bukan orang lain. Seperti tertuliskan pada Wawacan Ningrumkusumah dengan bahasa Sunda.
Budi pekerti geus tangtu, eta teh kudu diaji, tatabasa kasopanan, ilmu lahir ilmu batin, prak anggo salawasna, kanggo ngahargaan diri.
Budi pekerti sudah tentu, itu harus dipelajari, tata bahasa kesopanan, ilmu lahir ilmu batin, silakan gunakan selamanya, untuk menghargai diri (sendiri). (LXII Kinanti: 205. Alih bahasa oleh Ruhaliah, Perpusnas)
Bagi penulis, diam itu salah satu nilai dari budi pekerti yang tentu harus kita pelajari untuk kemudian kita berupaya menghentikan catcalling agar tidak terjadi di lingkungan kita. Mendekati seseorang dengan niatan untuk dijadikan pasangan hidup sekalipun tidak bisa dengan cara catcalling, tapi dengan cara yang baik, dengan budi pekerti. []